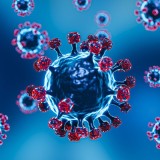TIMES KEDIRI, KEDIRI – Sesungguhnya masyarakat Indonesia memiliki kultur beradab dan berbudaya. Hal ini semakin tampak di wilayah Mataraman, Kediri, yang dikenal memiliki tingkat kepatuhan tinggi terhadap pemimpin formal maupun informal. Buktinya, dalam berbagai hajatan politik baik nasional maupun lokal, hampir tidak pernah terjadi konflik berarti.
Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Kediri sangat menghargai partisipasi, perbedaan pilihan, sekaligus menjaga tradisi guyub rukun, gotong royong, dan budaya kebersamaan sebagai perekat dalam mengawal demokrasi.
Seperti dikatakan Abraham Lincoln, demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, realitas hari ini menunjukkan adanya pergeseran partisipasi masyarakat menjadi dominasi elit.
Representasi politik yang semestinya milik rakyat perlahan berubah menjadi arena eksklusif kelompok kecil yang memiliki akses kekuasaan.
Dalam perspektif sosiologis, fenomena ini bukan hal baru. Teori elit meyakini bahwa minoritas kecil tidak terelakkan selalu mengendalikan mayoritas dalam masyarakat mana pun.
Konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir orang ini membentuk hampir semua aspek, mulai dari politik hingga ekonomi. Elit mempertahankan posisinya dengan cara menyerap penantang potensial dari kelompok bawah.
Alih-alih melawan, elit justru mengintegrasikan individu paling cakap dari strata sosial rendah ke dalam lingkaran mereka. Proses ini memiliki tujuan: menetralkan oposisi, membawa masuk talenta baru, dan menciptakan ilusi mobilitas sosial.
Para ahli teori elit juga berpendapat bahwa stratifikasi sosial adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Konflik yang lahir antara kelompok elit dan masyarakat bukanlah tanda disfungsi, melainkan gejala alamiah dari ketegangan antara yang berkuasa dan yang dikuasai.
Konflik ini justru punya fungsi penting: mencegah elit berpuas diri, membuka ruang sirkulasi kepemimpinan, sekaligus menjadi pemicu perubahan sosial.
Sejarah telah menunjukkan hal itu. Gerakan Hak Sipil di Amerika Serikat, misalnya, merepresentasikan pertarungan antara elit kulit putih yang mapan dan masyarakat Afrika-Amerika yang menuntut inklusi.
Integrasi beberapa tokoh gerakan hak sipil ke dalam lingkaran elit politik akhirnya menjadi bukti dari proses konflik dan sirkulasi sosial sebagaimana dijelaskan teori elit.
Jika ditarik ke konteks Indonesia, gejolak dan dinamika sosial yang terjadi saat ini, termasuk di Kediri, dapat dipetakan ke dalam beberapa faktor utama:
Pertama, akumulasi kesenjangan ekonomi. Ketimpangan antara elit dengan masyarakat sudah berlangsung lama dan mengakar dalam sistem politik. Partai politik dan parlemen kerap dianggap semakin jauh dari aspirasi rakyat, sehingga jarak sosial dan politik makin melebar.
Kedua, transparansi dan komunikasi publik yang lemah. Respons aparat, khususnya Polri, dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oknum sering dinilai lamban.
Contoh kasus tabrakan yang menimpa pengemudi ojek online menjadi bukti bahwa keadilan hukum sering berjalan lambat dan tidak transparan.
Ketiga, kinerja legislatif yang tidak responsif. Anggota DPR RI kerap gagal membuka ruang dialog terbuka dengan masyarakat.
Alih-alih menampung aspirasi, pendekatan yang ditunjukkan justru berbasis pengamanan dengan pagar aparat. Situasi ini hanya memperuncing emosi massa yang sedang bergejolak.
Keempat, perilaku hedonis pejabat publik. Gaya hidup mewah yang kerap dipertontonkan pejabat, di tengah kondisi ekonomi sulit, menambah jurang psikologis antara elit dan rakyat. Kepercayaan publik yang menurun kian diperparah dengan perilaku politikus yang tidak simpatik.
Kelima, lemahnya penanganan kasus korupsi. Kasus-kasus besar yang cenderung tidak tuntas melahirkan kesan bahwa hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Masyarakat sulit membangun kepercayaan penuh terhadap negara jika rasa keadilan terus dipertaruhkan.
Situasi ini membuat “nasi menjadi bubur”. Kepercayaan masyarakat yang rusak tidak bisa dipulihkan secara instan. Dibutuhkan waktu panjang, komitmen kuat, dan langkah nyata untuk mengembalikan legitimasi negara di mata rakyat.
Beberapa langkah cepat tentunya tetap bisa dilakukan. Pemerintah bersama DPR perlu segera mencabut pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset yang masih kontroversial, meninjau kembali tunjangan berlebihan bagi anggota legislatif, serta memangkas fasilitas istimewa lembaga negara yang timpang dengan kondisi rakyat.
Selain itu, komunikasi kinerja eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus diperbaiki dengan strategi sosialisasi yang elegan, intensif, dan transparan kepada publik.
Dengan begitu, demokrasi tidak hanya menjadi ruang dominasi elit, tetapi kembali pada ruh aslinya: mengedepankan partisipasi rakyat.
***
*) Oleh : Dr. Imam Fachruddin, M.Si., Sosiolog, Alumni Universitas Brawijaya, Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Kadiri.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |