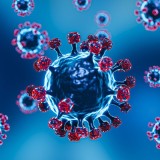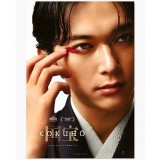TIMES KEDIRI, NUSA TENGGARA BARAT – Program Bantuan Langsung Tunai yang begitu populer masyarakat menyebutnya BLT yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Pada teknisnya, BLT dipahami sebagai kebijakan fiskal yang bertujuan memberikan dukungan finansial langsung kepada keluarga miskin.
Akan tetapi apabila dilihat dari sudut pandang genit dan nakal atau kritis, dengan berpura-pura menjadi Pierre Bourdieu sejenak, BLT sebagai fenomena yang lebih kompleks daripada “bantuan”.
Melalui apa yang telah saya sebut di atas sebagai genit dan nakal adalah cara untuk mengajukan sebuah pertanyaan tentang hakikat sesuatu, apa itu kemiskinan? Dan kemiskinan bukanlah sekadar penghasilan yang kurang. Kemiskinan adalah kondisi liquid yang mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang beradab, dan pengakuan sosial bagi semua warga negara. Sekaligus kemiskinan adalah realitas struktural, terdapat dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat.
Oleh karena itu, bantuan langsung tunai tidak dapat dilihat sebagai langkah terakhir untuk menghapus kemiskinan namun hanya dapat, paling tidak, menjawab tekan yang dihadapi kelompok katagori pandai dan piawai dalam kebijakan.
BLT yang dipastikan keniscayaannya, mempertajam tanda dimana negara mengakui keberadaan ketidakadilan struktural; mengakui bahwa sebagian warga negara tidak merasa mendapatkan bagian dari hak-nya secara merata.
Belantara tunai merupakan “pemberitahuan moral” bahwa negara mencakup kewajiban penuh memproteksi martabat individu masyarakat menjadi bagian dari negara itu sendiri. Namun, BLT tidak boleh dilihat sebagai upaya menyelesaikan akar penyebab kemiskinan sistemik. Melainkan tanpa reformasi struktural BLT hanya akan menjadi “obat linu jangka panjang”.
Pertanyaan yang menjadi penyertaan psikologi sosial, harkat martabat dan kekuasaan saat dibicarakan dalam kebijakan asas keadilan, suatu pertanyaan dasar: siapa yang tahu siapa yang miskin sebenarnya? Jelas, pemerintah, atau lembaga otoritas dengan mekanisme data DTKS, memiliki hak istimewa pengungkapan-pengetahuan untuk menentukan siapa saja yang memiliki hak atas bantuan.
Dalam pengalaman sosial, hal tersebut juga diakui bahwa data bukan selalu menjadi cermin realita, terkadang banyak yang bukan sasaran, banyak data ganda, atau data palsu, kemudian warga masyarakat yang “pantas” menerima tidak tercatat, sebaliknya yang mampu justru mendapat fasilitas.
Kemudian, pemangku kebijakan seharusnya memahami perbedaan “teknokratis” dan “lokal” pengetahuan, yang memperlihatkan ada kesenjangan epistemik. Pengetahuan negara biasanya sebagai eksternal, statistik, administratif, dan formal. Sebaliknya, masyarakat memiliki pengetahuan lebih lokal, menunjukkan sifat empiris berdasarkan relasi sosial dan pembacaan realpolitik untuk mendukung kehidupan sehari-hari konstituen.
Dengan demikian, epistemologi membutuhkan bahwa pengetahuan harus melalui proses pembuktian ketat dan terbuka dalam kebijakan dan melibatkan sebanyak mungkin sumber pengetahuan. Tanpa ketiga hal itu, mereka berisiko tidak hanya tidak efektif tetapi juga menciptakan luka baru dalam menunggu sebuah harapan keadilan dan kesejahteraan.
Nilai dan prinsip yang menjadi dasar perilaku manusia sebagai pelaksana kebijakan, maka dalam konteks BLT, unsur yang paling krusial adalah keadilan sosial. Dari sudut pandang utilitarianisme, kebijakan BLT bisa dianggap etis karena memberikan keuntungan besar bagi banyak orang, terutama di saat krisis. Namun, jika dilihat dari sudut pandang etika deontologis, BLT hanya dapat dianggap sah jika benar-benar diwujudkan berdasarkan tanggung jawab moral negara kepada warganya.
Jika menerapkan teori keadilan, BLT hanya bisa dianggap adil jika distribusinya ditujukan untuk memperbaiki keadaan kelompok paling rentan. Namun ketika BLT tidak mengenai sasaran, mengalir kepada pihak yang tidak berhak, atau ditentukan oleh faktor subjektif seperti kedekatan sosial atau politik, maka kebijakan tersebut beralih menjadi praktik yang tidak adil.
Lebih jauh, etika kebajikan mengingatkan bahwa kebijakan bantuan seyogianya meningkatkan nilai-nilai sosial seperti kemandirian, tanggung jawab, dan solidaritas, bukan menghasilkan ketergantungan yang pasif. Oleh karena itu, BLT harus ditempatkan dalam konteks nilai yang lebih luas; bukan hanya sekadar memberi uang, tetapi tentang menghormati martabat manusia, memperkuat integritas sosial, dan menegakkan keadilan.
BLT sebagai Instrumen Kekuasaan
Etika dan moral dalam dunia politik seharusnya dapat membantu memahami hubungan antara kebijakan publik dan kekuasaan. Menurut Michel Foucault, pengetahuan dan kekuasaan selalu saling terkait. Bantuan Langsung Tunai (BLT) bisa berfungsi sebagai instrumen biopolitik, di mana negara mengendalikan masyarakat melalui pencatatan, pemantauan, dan penyaluran bantuan.
Di satu sisi, ini mencerminkan perhatian negara, tetapi di sisi lain, BLT juga dapat berfungsi untuk memperkuat legitimasi politik dan mempertahankan stabilitas dalam kebijakan serta kekuasaan.
Sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki pandangan tajam, penting untuk menekankan komunikasi yang jelas tanpa adanya distorsi. Apabila BLT dirancang tanpa melibatkan masyarakat yang berhak berbicara, hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan, penolakan, dan konflik di dalam masyarakat.
BLT sebagai topik dalam sudut pandang nakal dan genit menunjukkan bahwa bantuan tunai bukan hanya sebuah metode dalam distribusi ekonomi, melainkan juga merupakan suatu tindakan moral dan politik yang menyentuh inti dari isu keadilan sosial.
BLT dapat menjadi alat yang efektif jika dilandasi oleh data yang tepat, nilai-nilai yang kuat, dan mekanisme yang melibatkan partisipasi. Akan tetapi, BLT juga bisa memperparah krisis keadilan sosial jika dilaksanakan tanpa adanya refleksi yang mendalam.
"Cinta terhadap kebijaksanaan" mengajarkan bahwa kebijakan publik perlu dibangun berdasarkan pemahaman yang akurat tentang manusia, pengetahuan yang valid, serta nilai yang mengedepankan martabat dan keadilan.
Oleh karena itu, BLT perlu terus dievaluasi agar tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sementara, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen negara dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil, manusiawi, dan bermartabat.
***
*) Oleh : Muhamad Maimun, Mahasiswa S3 UNUJA Paiton dan Dosen Prodi MPI IAI Qomarul Huda NTB.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
Artikel ini sebelumnya sudah tayang di TIMES Indonesia dengan judul: BLT dan Krisis Keadilan Sosial
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |